Tahun 1914. di sebuah rumah kayu tua di Lafayette Alabama. seorang bayi laki-laki lahir dengan kondisi keluarga yang pas-pasan.

Namanya Joseph Louis Barrow. Hidup nya nggak mulus sejak kecil.
Dari cerita orang-orang yang mengenal nya. dunia sudah keras bahkan sebelum dia belajar berjalan.
Ketika dia tumbuh. tubuh Joe membesar seperti anak kebanyakan. tapi tangan nya berkembang jauh lebih cepat.
Seolah-olah hidup mengajari nya bahwa untuk bertahan. dia harus punya senjata. dan itu adalah kepalan.
Bukan untuk sombong. tapi karena dia juga keluarga nya sering harus melawan keadaan.
Saat mereka pindah ke Detroit. dia menemukan tempat yang kelak mengubah hidup nya….pusat rekreasi kota.
Di sana. ruangan dengan aroma oli dan keringat. joe pertama kali benar-benar memukul samsak dan mengenal tinju.
Saya pribadi membayangkan suasana nya pasti sederhana..
lampu temaram. ring kecil yang sudah usang. suara pelatih yang tegas tapi peduli. dari situlah langkah Joe di mulai.
Waktu pertama kali naik ring sebagai petinju profesional. tidak banyak yang menyadari bahwa beberapa tahun kemudian. nama nya bakal dikenal di seluruh Amerika.
Bahkan rumah-rumah yang dulu terbelah soal ras dan kelas sosial. sama menyebut nama nya.
Namun yang membuat perjalanan Joe Louis di kenal orang bukan cuma gelar juara yang dia dapat.
Ada pertarungan nya dengan Max Schmeling tahun 1936 yang benar2 menjadi SEJARAH TAK TERLUPAKAN.
Schmeling. petinju Jerman yang cerdas dalam strategi berhasil membuat Joe takluk.
Kekalahan ini bukan cuma menyakitkan secara fisik. tapi juga menghantam perasaan banyak orang yang menaruh harapan pada anak muda kulit hitam yang sedang naik daun.
Saya pernah membaca tulisan seorang reporter New York Times yang bilang…
bahwa malam itu stadion terasa dingin. bukan karena cuaca. tapi karena suasana hati penonton.
Joe berjalan menunduk pulang seperti orang yang baru sadar bahwa dia sedang menanggung beban lebih dari pertandingan.
Kejadian itu di pelintir oleh banyak media di Eropa sebagai kemenangan besar bagi Jerman.
Schmeling sendiri sebenar nya tidak pernah minta di jadikan ORANG ISTIMEWA.
tapi situasi politik saat itu membuat pertarungan mereka terasa punya makna lain.
Dua tahun kemudian. kedua nya bertemu lagi. Kali ini suasana jauh berbeda. Joe tahu apa yang di pertaruhkan.
Orang Amerika pun tahu. Yankee Stadium malam itu penuh. sekitar tujuh puluh ribu orang menunggu balas dendam.
Dan Joe melunasi nya dengan cepat…
Dalam hitungan menit. Schmeling jatuh beberapa kali. wasit menghentikan pertandingan.
Komentator sampai berteriak-teriak menyebutkan betapa agresif nya Joe menyerang.
Saat hasil di umumkan. suasana berubah jadi pesta besar. Banyak yang menangis. berpelukan dan merayakan kemenangan Joe.
Dua menit di ring itu membuat banyak orang merasa bersatu. meski hanya sejenak.
Dalam pandangan saya… itulah salah satu momen terkuat dalam sejarah tinju. bukan karena KO nya dramatis. tapi karena orang yang biasa nya terpisah oleh perbedaan merasa berada di sisi yang sama malam itu.
Sayang nya. hidup Joe tidak terus berjalan seindah itu.
Ketika karir nya menanjak. beban yang dia tanggung juga makin berat. Bukan soal latihan atau pertandingan saja. tapi tekanan moral sebagai figur publik.
Banyak orang menaruh harapan besar pada nya. sementara Joe sendiri tetap mencoba menjadi pribadi yang rendah hati dan baik.
Dia membantu orang. menyumbang. dan bahkan meluangkan waktu menghibur tentara.
Tapi di balik itu semua. ada lubang besar yang pelan-pelan menelan hidup nya…
MASALAH KEUANGAN.
Zaman itu. atlet tidak di bekali pengetahuan keuangan seperti sekarang. Joe terlalu percaya pada orang di sekitar nya dan banyak keputusan yang tidak tepat membuat kondisi nya makin sulit.
Setelah Perang Dunia II selesai. masalah pajak menumpuk dan janji-janji pembebasan pajak atas donasi untuk kegiatan militer ternyata tidak jelas.
Semua tagihan jatuh ke tangan Joe dan angka-angka nya bukan main.
Ada satu cerita yang sering dikutip orang. Suatu hari Joe mengeluh lirih kepada seorang teman lama..
….Aku berjuang untuk negara ku. tapi sekarang negara ku menagih bunga dari pengorbanan ku.,,
Saya membaca nya pertama kali dan jujur saja sebagai penggemar tinju. rasanya seperti di tonjok kenyataan.
Seorang legenda yang pernah mengangkat nama bangsa justru kesulitan ketika karir mulai meredup.
Yang jarang di bicarakan orang adalah sisi manusiawi hubungan Joe dan Schmeling setelah pertarungan mereka.
Banyak yang mengira hubungan itu selalu panas. padahal kenyataan nya tidak sesederhana itu.
Schmeling sendiri setelah perang harus menjalani hidup di Jerman yang porak-poranda. menghadapi situasi politik yang rumit.
Di masa-masa setelah kedua nya tidak lagi bertanding. banyak sumber menyebut. bahwa mereka saling menghormati sebagai sesama atlet.
Bukan sahabat akrab yang teleponan tiap malam. tapi saling mengakui kemampuan satu sama lain.
Di dunia olahraga. kadang itu lebih berarti dari pada seribu kalimat manis.
Sementara hidup Joe makin berat. Untuk menutup utang yang menumpuk. dia kembali naik ring beberapa kali.
Tapi tentu saja tubuh nya tidak lagi seperti dulu. Penonton sudah berubah fokus ke petinju muda yang muncul di era baru.
Kekalahan-kekalahan yang datang kemudian semakin menunjukkan….
bahwa dia bertarung bukan karena ambisi. tapi karena kebutuhan.
Pada akhir nya.. Joe harus menerima pekerjaan sebagai penjaga pintu kasino di Las Vegas.
Ada beberapa foto yang beredar. menampakkan dia berdiri rapi dengan jas. menyapa tamu dengan sopan.
Bagi sebagian orang itu mungkin terlihat biasa. Tapi bagi yang tahu sejarah nya….
gambaran itu rasa nya keliwat PEDIH… seorang juara dunia. pernah di puja ratusan ribu orang. berakhir menyapa pengunjung slot machine.
Seorang mantan pegawai kasino bernama Mike Reynolds pernah mengatakan. bahwa Joe sering berdiri begitu saja. seperti orang yang hanya ingin ada yang masih mengingat siapa dirin ya dulu.
Saya bisa paham perasaan itu. dalam dunia olahraga profesional. tepuk tangan kadang berhenti lebih cepat dari pada rasa rindu.
Meski begitu..beberapa orang masih peduli. Frank Sinatra dan beberapa selebritas lain mencoba membantu sebisa nya.
Tapi biasa nya bantuan itu sifat nya sesaat. bukan solusi jangka panjang.
Sistem pada masa itu. memang tidak siap memberikan perlindungan ekonomi buat atlet besar.
Baca juga: Sejara sabuk Tertua di dunia, dari NBA bertransformasi ke WBA
Ketika kesehatan nya menurun. mulai dari masalah jantung. diabetes, hingga keluh tulang belakang. hal yang membuat banyak orang salut adalah dia tetap menjaga martabat nya.
Joe tetap ramah. tersenyum dan tetap menghormati siapa pun yang menemui.
Paling tidak. itu kesan dari banyak yang pernah bertemu denga nnya.
Suatu malam..seorang jurnalis muda bertanya apakah dia menyesal menjadi petinju.
Apa Jawaban joe louis?? Tidak… Tinju membuat ku melihat dunia. Hanya saja, dunia tidak selalu melihat ku kembali…
Kalimat itu menempel di kepala saya cukup lama. [Merinding tiap kali ingat kata2 ini].
Joe meninggal tahun 1981. Pemakaman nya di lakukan dengan upacara yang sangat terhormat di Arlington.
Itu semacam pengakuan yang datang terlambat. tapi tetap bermakna. Orang-orang yang dulu jadi saksi kejayaan nya datang memberi penghormatan terakhir.
Rasanya seperti dunia baru benar-benar sadar siapa Joe Louis itu setelah dia tidak ada.
Kisah Joe jangan di baca hanya sebagai cerita sedih…
Buat saya..justru banyak pelajaran yang relevan sampai sekarang.
Bahwa atlet perlu di bimbing dalam keuangan sejak muda. popularitas itu tidak selalu datang dengan perlindungan.
Seorang juara bisa kehilangan banyak hal kalau sistem di sekeliling nya tidak berpihak.
Hubungan nya dengan Schmeling juga menunjukkan sesuatu yang menarik..
dunia bisa mencoba mengadu dua orang sebagai alat politik. tapi pada akhir nya. dua petinju itu saling melihat sebagai manusia yang bekerja keras dalam bidang yang sama.
Pertarungan mereka tercatat dalam sejarah. sebagai salah satu duel terbesar.
tapi hubungan profesional mereka setelah itu memberi nuansa lain yang lebih HANGAT.
Sekarang. ketika generasi baru menonton ulang rekaman pertarungan klasik Joe Louis. mereka mungkin melihat KO. kecepatan atau pukulan kanan yang keras.
Tapi kalau di baca lebih dalam. cerita hidup nya mengajarkan bahwa ring tinju tidak pernah hanya soal menang atau kalah.
Ada keluarga di belakang nya. tanggung jawab. keputusan finansial. dan dialog panjang dengan kehidupan.
Pada akhir nya.. Joe Louis yang pernah menyatukan jutaan penonton hanya dalam dua menit.
menghabiskan hari tua nya mencari satu hal yang sebagian dari kita juga butuhkan….
tempat untuk merasa tidak DI LUPAKAN.
Terima kasih dan jangan lupa share artikel ini. biar mereka yang belum tahu jadi paham penting nya ASET MASA TUA.
agar kisah joe louis tidak menimpa pada kita di kemudian hari.
#JoeLouis #TinjuDunia #LegendaTinju #SejarahTinju #PetinjuAmerika #MaxSchmeling #KisahTragis




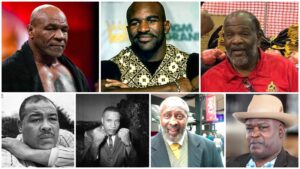





Pingback: Manny pacquiao vs floyd mayweather jr jilid 2??
Pingback: Joe Louis vs Buddy Baer, Duel Kontroversial Kelas Berat